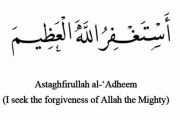Kisah nyata : Seorang ibu yang anti ulama’
Di masjid yang jama’ahnya relatif “heterogen”, saya biasanya menyampaikan beberapa pendapat ulama, dengan dalil-dalil mereka secara singkat. Tujuannya, agar kita bisa saling menghormati “perbedaan berdasar dalil” yang terjadi di tengah umat, apalagi jama’ah satu masjid.
Masjid tempat sejuk mencari ketenangan dan keberkahan, bukan ruang panas untuk menyatakan “pendapat saya yang paling benar”. Kita berhak mengikuti suatu madzhab, tapi tidak berhak memaksa orang lain untuk mengikuti madzhab dan pendapat kita. Tentu, selagi semua berdasarkan dalil normatif.
Namun, di tengah menyampaikan pendapat para ulama, ada saja yang masih menganggap:
• “Itu kan omongan orang”.
• “Harusnya Anda langsung mengambil dari al-Qur’an dan Sunnah!”
Seperti pagi itu, saat menyampaikan kuliah subuh rutin di salah satu masjid di kota Malang. Materi yang saya sampaikan adalah fikih, salah satu disiplin ilmu yang penuh dengan khilaf ulama. Saat saya sampaikan beberapa pendapat itu, tiba-tiba ada jama’ah putri mengajukan interupsi. “Ustadz, seharusnya Anda langsung merujuk pada al-Qur’an dan Hadits. Jangan kata orang, kata orang!”
Pernyataan semacam ini sekilas benar dan luhur. Namun sangat tidak elok bila tujuannya untuk mempertentangkan pendapat (baca: hasil ijtihad) ulama dengan al-Qur’an dan Sunnah. Orang awam diteror dengan al-Qur’an, diteror dengan Rasulullah: “Itu kan kata kiaimu, bukan kata Allah dan Rasulullah!”
Saya mengajak pengaju interupsi itu menalar secara mendasar logikanya untuk kembali pada Qur’an Hadits. “Baik bu, kita sepakat untuk merujuk pada al-Qur’an dan Sunnah. Tapi kalau misalnya ada dua hadits, yang satu shahih, yang satu dha’if, ibu pilih hadits yang mana?”
“Jelas yang shahih,” jawab beliau.
“Lalu, siapa yang mengatakan hadits ini shahih, hasan, atau dha’if? Al-Qur’an, Rasulullah, apa ulama, yang menurut ibu ‘kata orang’ itu?”
Beliau tidak menjawab.
Saya tidak bermaksud “menskak” beliau. Tapi memang “kembali pada al-Qur’an dan Sunnah” adalah tugas para ulama mujtahid, bukan orang awam seperti kita ini.
Kita memiliki banyak keterbatasan untuk langsung mengambil kesimpulan hukum dari suatu dalil (istinbath al-ahkam).
Nyatanya, status suatu hadits itu shahih, hasan, atau dha’if pun, adalah produk ijtihad ulama (orang), bukan kata al-Qur’an dan Sunnah. Maka, merujuk ijtihad ulama, bukan berarti meninggalkan al-Qur’an dan Sunnah. Wallahu a’lam.
( Ustadz Faris Khairul Anam )
Ingin bertanya permasalahan Agama? Kirimkan pertanyaan Anda kepada Tim Asatidz Tafaqquh Nyantri Yuk, klik http://tanya.nyantriyuk.id